“Warna” Wacana Cerpen Hajriansyah
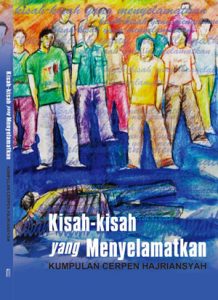 Sebagai sebuah tindak wacana, karya sastra, termasuk cerpen-cerpen Hajriansyah dalam kumpulan cerpen Kisah-Kisah yang Menyelamatkan (2016), bukan hanya merupakan representasi kebudayaan tetapi juga kritik terhadap kebudayaan. Cerpen Hajriansyah bukan hanya gambaran atau cermin pasif tentang sebagian kenyataan kebudayaan dan masyarakat tempat tinggal cerpenis tetapi juga sikap aktif cerpenis terhadap masyarakat dan kebudayaannya. Kondisi teks semacam ini menjadi ladang yang subur bagi ambiguitas, yang terbuka bagi banyak kemungkinan penafsiran. Tulisan ini hanyalah salah satu kemungkinan tafsir berdasarkan konteks yang saya pikirkan. Kumpulan cerpen ini memuat sepuluh cerita pendek (cerpen).
Sebagai sebuah tindak wacana, karya sastra, termasuk cerpen-cerpen Hajriansyah dalam kumpulan cerpen Kisah-Kisah yang Menyelamatkan (2016), bukan hanya merupakan representasi kebudayaan tetapi juga kritik terhadap kebudayaan. Cerpen Hajriansyah bukan hanya gambaran atau cermin pasif tentang sebagian kenyataan kebudayaan dan masyarakat tempat tinggal cerpenis tetapi juga sikap aktif cerpenis terhadap masyarakat dan kebudayaannya. Kondisi teks semacam ini menjadi ladang yang subur bagi ambiguitas, yang terbuka bagi banyak kemungkinan penafsiran. Tulisan ini hanyalah salah satu kemungkinan tafsir berdasarkan konteks yang saya pikirkan. Kumpulan cerpen ini memuat sepuluh cerita pendek (cerpen).
***
Cerpen “Telimpuh” menceritakan tokoh Ramin yang menjadi pusat perhatian rekan kerja dan istrinya karena merahasiakan “percintaannya” dengan Tuhan. Ia tampak telah lama meninggalkan salat, padahal ia tak ingin salatnya dilihat orang lain. Ia salat sembunyi-sembunyi. Ia menjadi simbol perlawanan bagi sikap keberagamaan yang kian narsis. Keberagamaan yang haus pengakuan dari sesama manusia. Ramin ingin lebih vertikal. Risiko ia harus ambil. Istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Cerpen ini tampak mendekonstruksi makna “haji”, “kaya”, “miskin”, “kebenaran”, “alim”, dan “cinta” yang serba tak pasti.
Cerpen “Tangan yang Menyelamatkan Aku” seperti meneruskan semangat Ramin secara lebih ekstrim. Cerpen ini agak sulit dipahami oleh umum karena tampaknya pembaca yang ditujunya adalah mereka yang akrab dengan terminologi tasawuf. Cerpen ini juga menyuguhkan konfigurasi bertasawuf yang ambigu. Tasawuf dipandang bukan sebagai hasil tetapi sebagai sesuatu yang terus berproses.
Cerpen “Kisah-kisah Tukang Urut” bukan hanya merepresentasikan budaya pijat di Banjarmasin tetapi juga menegaskan bahwa terminologi “urut” yang partikular di Banjar tidak sama dengan “pijat” yang universal di mana saja. Buktikan saja dengan mengetik kata “urut” atau “urut plus” di mesin pencari Paman Gugul. Hasilnya akan berbeda jika kita mengetik kata “pijat” atau “pijat plus”. Urut masih berada dalam denotasi, tetapi pijat telah memiliki banyak konotasi. Urut dan pijat bukan cuma soal kata di dalam kamus tetapi juga tentang nasib manusia di dalam kehidupan. Cerpen ini berbagi cerita pengalaman hidup dari dua tukang urut. Urut dalam cerpen ini dipandang bukan keterampilan yang hanya diperoleh dari belajar tetapi juga dari faktor juriat yang menurun. Selain itu cerpen yang ditulis pada 1435H atau 2014 ini mengabadikan sisi lain dari kondisi Banjarmasin sebagai kota yang memiliki memiliki beberapa hotel berbintang yang menyediakan layanan hiburan karaoke, ladies, dan alkohol.
Cerpen “Muara Sungai Kelayan” tampak ingin memperkuat representasi budaya Banjar dalam kaitannya dengan keterampilan yang diturunkan. Cerpen ini menyiratkan pesan bahwa juriat Banjar bukan hanya menurunkan keterampilan positif, tetapi juga kemahiran yang menjadi musuh publik, yakni maling. Cerpen ini menceritakan keluarga maling. Cerpen ini bisa menjadi alegori nasional yang sampai saat ini berjuang menghadapi korupsi. Bagaimana mungkin korupsi diberantas jika setiap hari kebudayaan kita terus melahirkan maling-maling baru secara sistemik? Maling dan kemiskinan terus menurun, dalam pengertian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maling dan miskin dua realitas yang saling berkelindan dan saling buru di negeri ini, termasuk di Kalimantan Selatan.
Cerpen “Tumbukan Banyu” menceritakan tokoh Maman yang bermimpi diburu kematian. Ia sangat ketakutan. Seperti lazimnya tokoh-tokoh dalam beberapa cerpen yang lain dalam kumpulan ini, ia juga lelaki perokok. Mimpinya tentu bukan mimpi setiap orang. Mobilitas Maman adalah identitas kelas dan mimpinya. Setelah setahun lewat, Maman akhirnya menemukan keberaniannya: berani mati dan bahkan menentukan waktu kematiannya.
Cerpen “Malam Kalang Hadangan” menceritakan tradisi mengembala kerbau rawa. Cerpen ini fokus pada deskripsi latar dan dialog tokoh mengomentari kehidupan peternak kerbau. Alegori empati budaya yang mungkin pula tidak tepat mewakili pihak yang disuarakan.
Cerpen “Lamut” menceritakan kehidupan seniman tradisi palamutan bernama Sebeh, keponakan palamutan Jamhar. Dengan alur episodik dan menceritakan lebih dari dua tokoh (Sebeh, Udin, Nyonya Lie), cerpen ini tampak ingin mereproduksi ingatan tentang pembauran Cina dan Banjar. Cerpen ini menjadi saksi perubahan sosial orang Banjar dan menegaskan bahwa Banjar itu tidak statis.
Cerpen “Buta di Rumah Pak Kasman” menceritakan Harum dan Peter yang bertandang ke Rumah Pak Kasman. Ceritanya terjadi di Jogja. Pak Kasman seorang penatah wayang yang tidak punya istri. Ia seiman dengan Peter: Katolik. Konfigurasi cerita persahabatan tokoh-tokoh tak seagama ini tentu menegaskan sikap penulisnya terhadap sikap eksklusivisme agama, ras, atau etnisitas. Jogja dijadikannya sebagai ruang terbuka pergaulan semacam itu. Perbedaan agama bagi Harum bukan perbedaan yang saling mengancam, tapi jadi hubungan harmonis yang saling menguatkan cita-cita kemanusiaan. Perbedaan adalah hikmah dan berkah. Bagi penyuka bacaan sastra multikultural, cerpen ini bisa jadi rujukan.
Cerpen “Dan Hari Terus Menuju Gelap” mengisahkan kehidupan pengusaha muda dalam lingkungan sosial yang hipokrit. Diceritakan dengan sudut pandang aku-an tunggal dan alur. Cerpen ini tergolong fiksi dengan alur yang tidak padu. Pembaca dibawa ke beragam cuplikan kisah dalam ingatan pencerita. Akhir kisahnya menunjukkan simpati pencerita, pengusaha muda, atas kecelakaan kerja yang menewaskan anak buahnya.
Cerpen “Sebuah Balon Berwarna Hijau” menceritakan secuil kehidupan Udin, penjual balon. Cerpen ini menggambarkan salah satu bentuk ketimpangan sosial dalam kasus pelayanan kesehatan untuk orang miskin. Udin dan tokoh-tokoh miskin yang lain tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Bahkan Udin merelakan anaknya meregang nyawa di rumah sakit.
***
Cerpen-cerpen Hajriansyah menggunakan teknik penyudutpandangan yang sangat variatif, yaitu sudut pandang orang pertama tunggal (aku-an), multi-orang pertama tunggal, orang ketiga (dia-an) serba tahu, dan gabungan sudut pandang orang pertama tunggal (aku) dan orang kedua tunggal (kau). Meskipun demikian, cerpen-cerpen dalam kumpula ini menunjukkan minat besar cerpenis pada tasawuf, semiotika budaya, mimpi, dan kebijakan kebudayaan. Kesan keseragaman tekniknya terletak pada beberapa cerita yang menggunakan model tokoh-tokoh yang bermimpi dan semua tokohnya adalah laki-laki (buruh, tukang urut, maling, seniman tradisi, peternak, pekerja advertising, penjual balon).
Keseragaman tersebut merupakan batas wacana dan representasi. Hajriansyah menawarkan makna dari identitas dirinya sebagai pengusaha muda yang peduli dengan seni tradisi dan seni lukis, pernah belajar tasawuf, punya kemampuan berkelana ke negeri-negeri yang jauh, bergaul dengan berbagai kalangan, dan tentu saja lelaki sebagai kepala keluarga dan perokok. Konfigurasi unsur-unsur cerpennya juga dipengaruhi pengalaman hidup penulisnya. Di hadapan pembaca dengan identitas pengalaman hidup yang berbeda, teks-teks Hajri dapat direspons berbeda. Pada titik inilah antara penulis dan pembaca dapat berdialektika tanpa perlu terus terjebak dalam apresiasi sastra yang penuh sanjungan puji dan puja.
Keberpihakan pada kelas sosial rendah menggalang sikap pembaca untuk memikirkan dan memperjuangkan orang-orang lemah dalam penindasan struktur sosial yang tidak adil tampak menjadi perhatian utamanya. Dengan demikian, kumpulan cerpen ini lebih menegaskan partikularitas budaya daripada universalitasnya. Cerpen-cerpen dalam kumpulan ini sangat segmented dan tidak cocok untuk semua umur (direkomendasikan untuk 17 tahun ke atas).
Jika cerpen “Telimpuh” diletakkan pada urutan pertama, mungkin karena secara naratif cerpen ini ingin dijadikan teladan bagi cerpen di bawahnya. Semangat realisme semi-revolusioner tampak pada cerpen-cerpen dalam antologi ini. Untuk benar-benar revolusioner, tokoh-tokoh yang bermimpi dan pasrah, pada cerpen selanjutnya mungkin perlu ditransformasikan menjadi tokoh-tokoh yang punya keinginan mengubah atau melawan struktur sosial yang tidak adil. Namun, mungkin pula ini sebagai bentuk prasasti literer tentang stagnasi kondisi sosial masyarakat dan bangsanya sebagai narasi besar penuh konflik, tanpa solusi, dan menyerahkan segalanya pada waktu: kondisi sosial tanpa agen perubahan sosial.
Rujukan
Mills, Sara. 1954, 1997. Discourse. New York: Routledge.